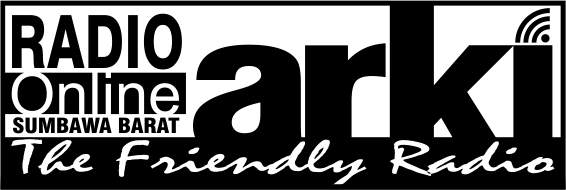Penulis: Siti Aminah, SH (Awardee Beasiswa NTB Tujuan Malaysia)
Bulan Maret merupakan bulan bersejarah bagi kaum perempuan. Pasalnya dalam penanggalan Gregorian yang bertepatan dengan 8 Maret 2021 diperingati sebagai International Womans day diseluruh belahan dunia.
Sejarah IWD
Cikal bakal Hari Perempuan Internasional berawal saat 15.000 pekerja perempuan di New York yang menyuarakan aspirasi mereka terkait pemangkasan jam kerja, upah yang layak, dan hak bersuara. Berdasarkan deklarasi dari Partai Sosialis, maka National Womans Day dirayakan untuk pertama kali pada tahun 1909 di AS.
Pada tahun 1909 diadakan konferensi Pekerja Perempuan International di Denmark yang dihadiri oleh 100 utusan dari 17 negara. Saat itulah seorang pemimpin Partai Demokrasi Sosial Jerman, Clara Zetkin mengajukan ide besar yaitu perayaan tahunan di setiap negara sebagai ajang untuk mendesak tuntutan mereka. Walhasil tahun berikutnya pada 19 Maret diperingati di beberapa negara yaitu Austria, Denmark, Swiss, dan Jerman. Selanjutnya pada tahun 1913-1914, perayaannya bertujuan untuk mengkampanyekan penolakan Perang Dunia I Pada tahun 1975 PBB mengesahkan tanggal 8 Maret sebagai hari Perempuan International.
Berdasarkan informasi dari internationalwomansday.com bahwa ada beberapa hal krusial yang di bahas yaitu : merayakan prestasi dan pencapaian perempuan, peningkatan kepedulian terhadap kesetaraan perempuan, akselerasi kesetaraan gender, dan menggalang dana untuk amal. Tema yang diangkat tahun ini adalah Choose to Challange yang berati bahwa, kaum perempuan harus berani memutuskan untuk menolak setiap stereotipe yang mendiskreditkan kaum perempuan, baik dari sisi ekonomi, hukum, sosial dan budaya.
Sudahkah perempuan mampu mengakses keadilan ?
Berbicara masalah tentang kesetaraan gender, maka identik dengan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya access to justice baik perdata maupun pidana. Diantara regulasi yang dianggap kontra-perempuan yaitu, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Banyak yang berpendapat bahwa istilah kepala keluarga di dasarkan atas ayat Al-qur’an Q.S An-Nisa (4) : 34 yang berbunyi ar-rijaalu qawwaamuna ‘ala an-nisa yang artinya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Tentu tidak serta merta ayat tersebut dipahami hanya dari teks ayat, melainkan juga kontekstualisasi makna literal dan tujuan ayat. Adapun interpretasi kata pemimpin dalam redaksi ayat tersebut mencakup 2 syarat, yaitu : pertama, dominasi seorang suami atas istri baik dari sisi agama, intelegensi, moral, dan finansial. Kedua yaitu diberikan kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin karena memiliki kelebihan atas yang lainnya berupa pemberian nafkah. Lalu bagaimana jadinya jika suami tidak mampu memenuhi kedua hal tersebut ?
Masih di Undang-Undang yang sama, selanjutnya pada pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami dan Istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Berdasarkan pasal diatas, dapat diketahui bahwa ada upaya melegitimasi secara mutlak tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Tetapi yang menjadi titik fokus adalah ayat (2) yang mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini seolah terlalu mencampuri ranah privat warga negara. Karena secara fakta empiris, ada begitu banyak keluarga yang tidak sejalan dengan harapan Undang-Undang Perkawinan. Suami yang seharusnya memberikan nafkah malah membebankan pemenuhan kebutuhan pangan pada istri. Sebaliknya suami yang di rumah dan istri yang bertebaran di ranah publik demi mencari rezeki untuk mereka dan anak-anaknya. Sehingga menjadi suatu kekeliruan jika melekatkan suatu bidang hanya pada jenis kelamin tertentu. Keduanya berhak memaksimalkan prestasi yang dimiliki.
Selain itu, persoalan pidana pun tidak luput dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menditribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal karet ini telah mengorbankan nasib seorang guru di Mataram. Siapa yang tidak ingat kasus ibu Nuril, korban pelecehan seksual sang kepala sekolah. Demi menjaga harkat dan martabat serta membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sebaliknya menjadi korban maka ia pun merekam pembicaraan tak senonoh atasannya itu. Tetapi karena rekaman tersebut tersebar luas, kepala sekolah tersebut pun geram kemudian melaporkan Baiq Nuril dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr menyatakan ia tidak bersalah. Namun nahas, Mahkamah agung pada putusannya nomor 574 K/Pid.Sus/2018 memutus ia bersalah dan dikenakan pidana penjara 6 bulan dan denda 500 juta. Meski pada akhirnya ia bebas dari jerat hukum karena amnesty dari Presiden. Tetapi hal ini menunjukkan kelemahan dari pasal tersebut yang multi tafsir sehingga dalam hal ini tendensi dari aparat penegak hukum akan melihat dari sisi positivistik-legalistik saja. Padahal sebenarnya hukum itu melayani warga negara. Hendaklah dilihat dari hukum progresif yang mana hakim tidak selalu terkungkung hanya pada teks undang-undang semata, melainkan dengan keyakinan memberanikan diri mengekslusikan diri dari tatanan demi menemukan nilai-nilai humanis untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Adapun opsi terbaik demi mencapai kata adil hanya merevisi kembali regulasi tersebut, agar tidak terjadi konservatisme yurisprudensi yang pada akhirnya mengorbankan rakyat.