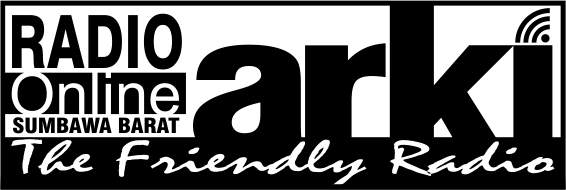Sajak cinta sudah terberi. Bahkan, melimpah ruah. Sajak otentik, ataukah palsu. Bukan urusan KITA. Resiko jadi Bupati. Dicinta, tanpa perlu harus mencintai.
Puisi cinta. Sastra cinta. Kerja cinta. Bahkan kritik juga cinta. Bukan cinta, tatkala dilecehkan, dihina, apalagi merongrong soal privat. Rakyat yang berikan itu. Resiko jadi Bupati, siap harus menerima cinta. Tanpa harus mencintai.
Disana ada harapan, disana ada perhitungan, disana ada kemewahan, disana ada kegembiraan. Disana berlabuh semua cita, cinta, harapan, kegelisahan, kritik, bahkan kebencian. Sebagai pelabuhan, ruang dan tempat harus tersedia. Ikhlas ataukah terpaksa. Karena itulah Bupati kita, pelabuhan kita. Harus menampung. Dipakai, didiamin, ataukah dibuang.
Cinta dan benci bergandengan. Nurani dan kepentingan diri, berkontestasi tajam. Hingga tiba, mana posisi yang berbuah ‘kenikmatan’. Soal prinsip dan idiologi, hanyalah pilihan privat. Iya soal privat.
Di hari yang serba mahal. Serba bisa dijual. Serba bisa dijadikan proyek, asal jadi, asal ngomong, asal senang, sangatlah lumrah. Gak ada yang perlu “KITA” kaget.
Dikala KITA semacam hutan rimba. Logika hutan menancap TAJAM. Kita cenderung tidak peka mentukan arah. Sama semacam logika hutan gundul. Sebelum gundul adalah proyek, setelah gundul juga proyek. Tetap saja “KITA” termonopoli proyek. Kita adalah proyek. Siapakah kita? Saya, anda, orang tua, keluarga, dan kita. Kita adalah proyek. Apakah ini disebut masyarakat? Jawaban sederhana, iya. Apakah mereka tidak mau berhenti, menurut saya tidak. Tugas mereka merawat kesenjangan karena ketimpangan. Karena itu adalah Proyek.
Kita hanya perlu melatih untuk siap. Siap menerima ketimpangan. Dan merasakan kesenjangan. Dan menunggu kapan waktu yang tepat, mengkonversi menjadi keuntungan. Disini mereka tidak lagi narator tunggal. Ada banyak pemain masuk, langsung ataukah pengganti. Yakin rakyat diprioritaskan, saya tidak. Sebelum Bupati menjadi milik kita. Bukan milik mereka.
Umi Dinda Bupati kita. Bukan monopoli Golkar. Bukan kepunyaan istana. Apalagi hak paten keluarga, kolega, dan tim sukses. Bupati milik petani jagung, padi, bawang, garam. Milik guru, nelayan, buruh, penjual sayur. Termasuk milik tukang bakso, tukang parkir, imam mesjid, pastor. Intinya Umi Dinda milik kita, karena dia Bupati kita.
Bupati kita memayungi semua warna. Kuning bukan warna Bupati. Biru, jingga, merah, dan hitam juga warna yang harus terpayungi.
Dia tidak perlu turun tangan, hanya untuk memastikan kuning dapat proyek apa, merah jatahnya berapa, hitam tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga tidak perlu jadi tani, buruh, nelayan, dan tukang parkir. Hanya perlu memastikan, mengapa dapat apa, apa untuk apa, dengan keberpihakan yang sama. Bupati itu kita, kita adalah bagian dari Bupati. Gak boleh dibedakan, pengakuan terhadap pedagang kaki lima, dengan perusahaan raksasa alfamart. Apalagi, membunuh nalar rakyat bawah, untuk menyelamatkan kaum pemodal. Dengan alibi kesejahteraan, yang memangkas kewarasan. Kewarsan kita.
Kita tidak menganggu waktu, untuk jalan-jalan melepas gundah dan jenuh. Karena bosan, atau berlebihan dalam mengabdi. Kita tidak mengusik ranah, privat. Kita hanya berusaha berharap, bahwa kita sama. Sama-sama membutuhkan cinta, menggapai harapan. Yang dibutuhkan kita, dilihat dengan kedua mata, tanpa harus menutup salah satunya. Didengar dengan kedua telinga, dirasakan dua hati, disampaikan dua tangan dan kaki.
Saat satu dua gedung tumbuh megah, ditempat lain, maka tidak perlu penggusuran ditempat lainnya. Saat padi mulai menguning ditempat lain, maka tidak mesti ditempat lain, nurani menangis karena bahan untuk dibuat nasi, sukar dicarai.
Setiap diksi pinjaman, memerlukan pembiayaan yang dipinjam. Setiap visi yang tidak otentik, memerlukan realisasi yang tidak otentik. Rekayasa dan kalkulasi berlaku.
Nalar terpaksa tertunduk, ataukah melawan. Tergantung idiologi dan pengamatan. Apakah kita lihat, kondisi baik-baik saja. Disetiap ada asap pasti ada api. Kita hanya perlu mendeviniskan, rumah kita baik-baik saja, ataukah sedang terbakar. Saya melihat sedang terbakar. Sedang terbakar. Sedang terbakar. Menyala tidak terlalu kelihatan, mendamaikan juga tak kunjung redam.
Kita lihat, biaya dari rakyat untuk negara, untuk dilayani kepentingan memerlukan darah, tangis, dan uluran tangan dan CALO. padahah saat dibiaya mereka tidak perlu mengulurkan tangan, isak tangis, keringat, dan Calo.
Biaya untuk melayani, sangatlah mahal. Seperti menyewa pembantu rumah tangga, untuk membersihkan rumah, rumah tak kunjung bersih. Tapi malah bertambah kotor. Tiba-tiba pelayan berlaku kayak DEWA. Yang dilayani, malah semacam BUDAK. Itu bukan Bupati kita, tapi Bupatinya mereka.
Terlalu banyak soal. Mulai dari rumah, sampai pada jembatan yang menghubungkan rumah. Saya bosan, jenuh, dan gundah tapi siapakah saya, siapakah kita. Apalah daya?. Belum selesai, yang satu, muncul lagi soal dua, sampai seterusnya, berputar-putar, sampai menghilang. Karena dari awal proyek, jadilah proyek terusan. Dan kita dipaksa menonton, melotot, mengagumi pementasan drama apik, yang sebenarnya membosankan. Mereka pandai memoles diri, merekayasa diri, seolah baik-baik saja. Kita dipaksa waras dengan hal dan cara mereka yang merusak kewarasan.
GANTI BAJU
Dari waktu ke waktu. Drama dipentaskan. Diulang-ulang. Pemainnya sama. Korbannya sama. Tampilan, dipercantik. Sedemikian rupa. Sedemikian sexi. Yang untung itu-itu saja.
Baju diganti berulang-ulang. Pemakai baju itu-itu saja. Baju itu membungkus ketimpangan, kesenjangan, kebobrokan, korupsi, kolusi, nepotisme, mark-up. Anehnya kita menilai mereka cantik, gagah, dan rupawan.
Napi koruptor, dispesialkan, penjilat disanjung-sanjung, korupsi tak kunjung selesai, pembangunan dirundung nestapa, ketimpangan semakin hari kontras. Standar like and dislike dibakukan, relasi kuasa dikukuhkan, dan kita harus menyaksikannya.
Adakah yang tidak gundul. Adakah yang masih ontentik, adakah keberterimaan, adakah keikhlasan.
Jalan-jalan. Suka ria. Penuh senyum. Penuh bangga. Adakah yang perlu dirindukan. Adakah yang perlu dirawat ingatan. Ataukah kita lupa ?
Teks memang indah. Apalagi disampaikan dengan mimik sedih dan penuh semangat. Apakah cukup persoalan kita diselesaikan dengan teks, yang dramatis itu.
Bagaimana kalau teks indah hanya bisa terucap, tapi tidak bisa dibaca. Hanya dengan menjadikan, Bupati itu milik kita, kita bisa berharap persoalan bisa dijawab, kemajuan disambut, dan optimisme menyala. Dalam drama, kita perlu mendapatkan tontonan yang otentik. Seperti tersenyum dalam mengurai prestasi, mengurai ketimpanganpun harus terucap dengan senyuman.
Saat kita bisa jujur dan bangga, karena kemajuan, kita berhak mendapatkan kejujuran dan bangga mendengar masalah ketimpangan yang terucap. Dari Bupati kita. Milik bersama kita.
Umi Dinda Bupati Kita
Satria Madisa
Mataram, 28 November 2018