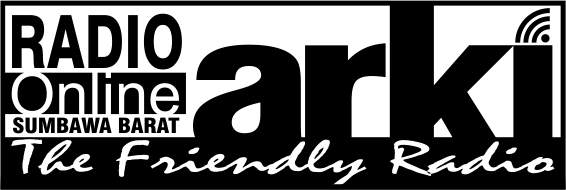Gugatan yang dilayangkan paslon BEM Unram nomor 2 kepada penyelenggara Pemira Unram 2019 (KPRM dan DPM Unram) akibat terjadinya aksi anarkis mahasiswa FT menyerang mahasiswa FH di FH Unram yang berbuntut jatuhnya korban dan tertekannya penyelenggara pemira hingga diambilnya sikap penghitungan suara secara sepihak oleh paslon Bem Unram nomor 1 (Amri – Mandele) tanpa melibatkan paslon nomor 2 (Zaki – Hudian), sampai hari ini masih melahirkan banyak narasi dari para mahasiswa.
Hal tersebut terbukti dengan adanya perdebatan panjang FB an Wawan Suryadi dengan FB an Didi Muliadin di status/tulisan FB Wawan Suryadi yang berjudul “Aspek Hukum Wacana Upaya Hukum Gugatan Pemira Unram 2019”. Tulisan yang dihajatkan mencerahkan publik, yang katanya obyektif. Setelah dibumbuhi dengan perdebatan, alhasil lama-lama semakin memperlihatkan sisi subjektif yang inheren akan beberapa komentar apologinya.
Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa perdebatan tersebut ditenggarai oleh tulisan Wawan di FB-nya. Di mana ia ingin meluruskan langkah paslon nomor 2 yang dianggapnya keliru. Padahal jika ditelaah dengan seksama dari “causa prima” tulisannya, yang gagal paham itu ialah dirinya sendiri.
Betapa tidak, Wawan kurang teliti dalam membaca berita terkait dengan gugatan paslon nomor 2. Ia mengira paslon tersebut akan mengajukan gugatan atas kekacauan Pemira ke PTUN. Padahal hanya menggugat KPRM atas kejanggalan-kejanggalan pemira dengan mengeluarkan surat gugatan kepada Ketua KPRM.
Memperhatikan tulisan Wawan, kita bisa saja mengira ia terlalu over-abstraksi dalam menyerap dan menanggapi gugatan paslon nomor 2. Sehingga ambivalen dari hal obyektifnya. Jika menggunakan Logika seperti Didin, dapat dilihat bahwa subtansi tulisan tersebut memang tepat namun tidak benar. Tepatnya; jika pihak birokrasi tidak menggapi gugatan yang dilontarkan paslon nomor 2, maka bisa ditempuh jalur PTUN. Tidak benarnya: paslon nomor 2 tak membutuhkan SK BEM untuk menggugat secara PTUN, karena DPM (sebagai bagian penyelenggara yang membentuk KPRM juga di SK-kan oleh birokrasi), dan untuk gugatan ke KPRM yang dibuatnya Zaki-Hudian dan terekspos di beberapa media tidak tertera akan membawakan masalah tersebut ke PTUN.
Sekalipun maksud Wawan mencerahkan, bahkan jauh memandang ke depan dengan jalan berpikir. Namun tidak dipungkiri kebutuhan publik adalah didapatkannya pengetahuan yang benar, bukan hanya tepat. Dan untuk hasilnya yang benar itu harus tersedia bahan-bahan yang benar sesuai dengan obyeknya. Sehingga tidaklah salah kita dalam merumuskan pengertian, putusan dan penuturan dalam menyoroti masalah tersebut sesuai dengan kaidah logika.
Tetapi tak dipungkiri. Apabila bahan-bahan yang digunakan Wawan pada awalanya keliru, logika masih bisa membentuk darinya tujuan yang tepat tapi tidak benar. Seperti pada maksud lain tulisannya; “jika gugatan paslon nomor 2 ditolak birokrasi, maka paslon nomor 2 harus menggugat secara PTUN, karena sudah keluar SK BEM.” Menurut logika penuturan itu adalah tepat. Tetapi apakah benar? Penuturan itu tidak mengatakan, bahwa gugatan paslon nomor 2 ditolak birokrasi, melainkan “jika”. Oleh karenanya, hal tersebut menegaskan ada ketidakbenaran dalam alur pikiran Wawan sehingga Didi menyebutkan dalam beberapa komentarnya tidak konsisten dengan surat gugatan obyektif paslon nomor 2.
Jadi jelas bahwa seharusnya logika yang Wawan pakai menghasilkan pengetahuan selain tepat juga benar, manakala bahan-bahan yang pakai sedari awal untuk merumuskan pengertian, menuangkan putusan dan menceritakan penuturan menurut kaidah-kaidah logika itu benar atau obyektif sesuai dengan surat gugatan paslon nomor 2 yang sebenarnya — surat gugatan ke KPRM. Tapi dalam pengertian, putusan dan penuturannya unsur yang terpenuhi hanyalah logika formil (ketepatan), sementara logika materiil (kebenaran) tidak dipenuhi.
Tidak cukup sampai di situ, bertolak dari tulisan Wawan itu, penulis ingin menambahkan bahwa jikalau diadakan pemilihan ulang sebenarnya bukan merujuk akan mampukah TPS FH Unram melampui suara yang sudah didapatkan paslon nomor 1, sebab itu bukanlah tujuan obyektifnya. Tetapi lebih kepada obyek suatu masalah, Yaitu: mahasiswa hukum sebagian tidak memilih dikarenakan keributan yang dilakukan Mahasiswa FT di FH, makanya membutuhkan pemilihan ulang agar mahasiswa yang belum memilih juga ikut memberikan suaranya.
Barangkat dari itu juga, apa yang dipikirkan Wawan adalah tepat sebab satu fakultas suaranya lebih sedikit dibanding 8 fakultas lainnya, namun pendangan tersebut sekali lagi tidak benar. Dan pikiran ini pun menandakan subyektifitas dan jika boleh dikata, akibat ketidakbenarannya menandakan adanya kecondongan Wawan pada salah satu paslon.
Baiklah Wawan, begitu sederhana yang ingin saya tuturkan. Yaitu membedakan antara yang benar dan tepat. Karena sesuatu yang benar adalah tepat. Tetapi yang tepat belum tentu benar. Jika ilustrasi saya yang di atas masih belum cukup menggambarkannya. Akan saya tambahkan; teman saya seorang buruh pabrik di Mataram, tinggal di Sumbawa, harus naik motor dan menyebrang dengan kapal laut untuk sampai ke Mataram tiap hari mengeluarkan uang bensin dan kapal 4 x Rp 30.000 sebulan rata-rata Rp 360.000. Sedangkan gajinya sebulan hanyalah Rp 350.000. Akhirnya ia sering tidak masuk, demi mencari pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan sekaligus untuk penunjang ongkosnya ke pabrik. Karena sering membolos, kepala pabrik menghukumnya. Gajinya dikurangi. Nah, sekarang timbul masalah akibat keputusan itu. Bagaimana sifat keputusan itu? Keputusan itu tepat, tetapi tidak benar. Tepat karena sesuai peraturan yang berlaku. Pegawai yang sering bolos dijatuhi hukuman untuk mencegahnya bikin kesalahan lagi dst. dst.. Tetapi keputusan itu tidak benar. Ia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, guna memberi makan keluarganya. Jangan ongkos makan, biaya ke kantor saja dia defisit. Jadi menurut kenyataan keputusan itu tidak benar. Itu ilustarasi sederhananya.
Karenanya, jika Wawan mampu melihat ketidakbenaran dalam berlogikanya, sudah sewajarnya memahami apa yang dikatakan Didi dalam komentarnya. Bukan malah memberikan analogi antara rezim pemilu dengan pilkada yang tentunya menimbulkan kesimpangsiuran esensi dari pembahasan. Olehnya, selain ditegaskan kembali selain diperkatakan logika ialah penuturan itu tepat. Ia pula membutuhkan kebenaran, dengan menarik kesimpulan dari premis yang benar, yakni mengatakan dengan keadaan yang sesungguhnya.
Selain itu, pada kolom komentar-komentar dari tulisan Wawan diarahkan menjadi sangat irelevan dengan esensi persoalan. Sebab, apa yang dikatakan oleh Didi, “pemira dan pemilu tidak bisa dikomparasikan secara sistematis,” memang benar. Pemira adalah pesta demokrasi mahasiswa (rakyat di kampus), sebagaian “bayangan” dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pengertian ini adalah tepat, karena pengertian sebagian dapat masuk dalam pengertian umum. Karena pemira merupakan contoh semu pemilu, dapatlah dikatakan ia pesta demokrasi (rakyat di negara) seperti pemilu. Tetapi pesta demokrasi pemilu tidak dapat disamakan dengan pemira. Sebab pemira merupakan sebagian contoh (partikular) dari pemilu (universal). Dan jika pemilu proyeksikan ke bulatan yang univesal atau luas, sangatlah tidak mungkin masuk ke bulatan pemira yang partikular atau sempit. Begitulah logikanya, sehingga sangatlah kontras bahkan congkak dengan esensi bahasan.
Atau jika masih kurang jelas, penulis berikan lagi ilustrasi kenapa yang umum tidak bisa masuk dalam yang sebagian. Seperti; kerbau adalah hewan. Jalan pikiran ini sangatlah tepat karena pengertian sebagian (kerbau) dapat masuk ke yang umum (hewan). Karena kerbau sebagian dari hewan dapatlah kita katakan dia hewan. Tetapi kita tidak bisa katakan setiap hewan itu adalah kerbau. Karena yang universal/luas tidak bisa masuk ke dalam yang partikular/sempit. Dan merujuk pada peranan isi pada logika, konflik pada pemira tidak bisa diambil penyelesaiannya seperti pada pemilu dan tak boleh dikomparasikan secara sistematis dengan pemilu karena akan menimbulkan kerancuan.
Dengan demikian dalam membahas terkait gugatan Pemira BEM Unram 2019 begitu sulit kita menggunakan logika secara konsekuen. Sebab, dalam aturan berpikir tepat dan benar tersebut mengharuskan suatu obyek bahasan yang statis — memiliki dasar aturan yang jelas (peraturan penyelesaian konflik pemira, agar dapat diselesaikan. Jika tidak ada maka sukar diselesaikan dengan logika). Sehingga dalam persoalan tersebut adalah suatu masalah yang tidak statis, tetapi memiliki sifat yang menuntut pada suatu dinamika.
Apalagi asas identitas pada logika memastikan A=A (pemira itu pemira/gugatan KPRM itu gugat KPRM, B=B (pemilu itu pemilu/gugatan PTUN itu Gugatan PTUN). A di samping A tidak mungkin menjadi B dan sebaliknya. Kaidah-kaidah pengertian, putusan dan penuturan memastikan ya itu ya dan tidak itu tidak. Jadi suatu pertanyaan dihadapkan kepada logika pasti dijawab dengan alternatif ya atau tidak. Namun, pertanyaan mengenai gugatan tersebut sukar dijawab dengan iya atau tidak. Apabila logika sudah tidak mampu menjawabnya. Sudah sewajarnya dialektika dipakai.
Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Dalam pengertian sehari-hari dialektika diartikan pula kecakapan melakukan perdebatan. Dalam teori pengetahuan, dialektika merupakan bentuk pikiran berupa percakapan (tulisan/komentar) percakapan yang bertolak dari dua kutub seperti yang dilakukan Wawan Suriadi dan Didi Muliadin saat ini. Tetapi, jika tetap menggunakan perbandingan dari pemilu tentang wewenang MK menyelesaikan konflik pemilu, atau keharusan pembentukan lembaga dalam menyelesaikan konflik pilkada. Itu sama halnya komparasi-komparasi yang dilakukan masih terjebak dalam lapangan logika, yaitu mencoba melakukan induksi dari konflik pemilu/pilkada kemudian deduksikannya kepada pemira.
Sedangkan, yang dibutuhkan untuk membahas persoalan gugatan pemira ini adalah pembahasan dengan menggunakan kaidah dialektika yang meliputi lapangan waktu, saling hubung, pertantangan dan gerak dengan jalan pikiran perubahan. Dan pembahasan-pembahasan itu bertolak dari asas logika berupa kenyataan obyektif yang terjadi, bukan terjebak pada komparasi-komparasi yang memperlebar bahasan awal. Sebab, menjerumuskan pada pengetahuan-pengetahuan yang keliru (masa sampai Judicial Review, yang semuanya terfocus pada pemilu dan bukan lagi membahas persoalan KPRM. Apalagi, sampai memasukan persoalan yang hiperbola dari pangkal masalah; biaya keberangkatan dan segala ongkos lainnya. Jujur Bung Didi, Bung Wawan, dari beberapa hari yang lalu saya terus memantau perkembangan diskusi kalian. Semulanya, karena kalian orang FH Unram, saya beranggapan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Eh, ternyata malah kalian menambah kompleks persoalan — yang simpel menjadi rumit, sampai ada penyerangan karakter).
Tak mau mengingkari budi, pembicaraan kalian atas dua sudut pandang yang bertentangan seharusnya membawa pada paradigma dialektika. Sebagai misal kembali lagi kepada contoh seorang buruh pabrik yang saya deskripsikan tadi. Karena gajinya untuk ongkos ke pabrik saja tidak cukup, sering membolos untuk kerja serabutan. Kemudian kepala pabrik menghukumnya. Dipandang dari logika keputusan atasannya itu tepat, tetapi tidak benar karena tak sesuai kondisi. Lantas bagaimanakah dialektika memandang itu?
Adilkah putusan atasan itu? Dengan pandangan dialektika tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Dipandang dari dari sudut pandang atasan: adil. Kenapa? ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dipandang dari segi buruh pabrik: tidak adil. Mengapa? Tidak sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang berlaku. Gajinya Rp 350.000. Ongkosnya ke pabrik Rp 360.000. Ini saja sudah tidak adil. Ia kerja untuk menafkahi keluarga. Jangankan makan bisa dibeli, ongkos saja sudah defisit. Beberapa kali ia bolos untuk mencari uang menutupi kekurangan itu, sehingga ia pun bisa tetap pergi kerja ke pabrik. Seharusnya atasannya berterima kasih atas kesetiaanya ke pabrik. Tetapi malah dihukum. Adilkah itu?
Dan jika dipandang dari segi buruh pabrik keputusan itu tidak adil. Dengan demikian ada dua sudut pandang. Dalam pandangan pertama berlaku sebagai tesa, dan yang menjadi antitesa. Maka dialektika memutuskan sintesa keduanya itu. Berdasarkan ekonomi NTB, gaji si buruh harus dinaikan sehingga bukan saja ongkos ke pabrik dapat ia penuhi, juga keluarganya memperoleh makan dari hasil kerjanya. Dan berdasar aturan pabrik, ia digaji untuk bekerja bukan membolos. Tiap hari harus datang ke pabrik untuk bekerja. Dus, sintesanya adalah gajinya dinaikan dan setiap hari ia wajib bekerja di pabrik.
Sintesa itu dalam pemikiran dialektika selanjutnya menjadi tesa baru. Muncul lagi antitesa, pabrik menolak kenaikan gaji. Pegawai terlalu banyak, sedangkan pendapatan negara sedikit, tidak mampu menaikan gaji buruhnya. Sintesanya: sebagian buruh yang malas bekerja (atau buruh tidak tetap) diberhentikan, sehingga jumlahnya berkurang, dan dari pendapatan pabrik yang ada bisa digunakan untuk menaikan gaji buruh yang rajin bekerja.
Baiklah kawan-kawan; Bung Didi, Bung Wawan. Perdebatan atau komentar-komentar kalian sungguh menakjubkan, sayang terjebak pada wacana judicial review (rezim pemilu/pilkada) dan kurang mampu bertolak ke pemira lagi secafa obyektif sesuai yang dibutubkan paslon nomor 2. Tetapi, kita telah sama-sama tahu bahwa pangkal persoalan kita adalah membahas mengenai gugatan paslon nomor 2 ke KPRM atas konflik pemira (kekerasan fisik kepada mahasiswa FH Unram oleh timses paslon nomor 1 dari FT Unram dan kekerasan simbolik yang termanifeatasi oleh penghitungan suara secara sepihak oleh paslon nomor 1 tanpa melibatkan saksi, timses dan paslon nomor 2).
Bertolak dari kejadian obyektif yang terjadi. KPRM dibentuk oleh DPM dengan berdasar SK birokrasi. Apalagi KPRM membuat dan mempunyai aturan dalam pelaksanaan pemira. Dengan terjadinya penghitungan suara sepihak oleh paslon nomor 1 dan kekerasan yang tenggarai serangan paslon nomor 1 ke FH Unram, membuat paslon nomor 2 mengeluarkan surat gugatan untuk KPRM sebagai penyelenggara pemira agar menindaklanjuti konflik pemira. Tetapi karena tidak adanya lembaga atau aturan penyelesaian konflik pemira, maka untuk menyelesaikan konflik itu harus melalui PTUN dengan menggugat SK BEM Unram yang dikeluarkan birokrasi. Dari sudut pandang asas legalitas memang itu hal yang tepat. Tetapi bagaimanakah dengan keinginan paslon nomor 2 menggugat KPRM (terkait kebenaran aturannya, terlebih wewenangnya sebagai pembuat aturan pemira), bukan SK BEM-nya, apalagi setelah dibawa ke TUN wewenang lembaga manakah nantinya yang akan menangani konflik pemira di saat rezim pilkada dan pemilu saja hingga hari ini dalam penyelesaian konfliknya mengalami banyak masalah? Ketika penyelesaian konflik di PTUN nanti berlarut-larut, bagaimana nasib paslon nomor 2 yang hanya ingin menggugat aturan KPRM (dan bagaimanakah nasib mahasiswa Unram, mengalami kekosongan pimpinan). Adilkah itu?
Pada paparan di atas, yang pertama sebagai tesa dan yang kedua menjadi antitesa. Olehnya pemikiran dialektik memutuskan sintesa, dengan melihat kebutuhan politis mahasiswa, KPRM yang belum bubar itu yang mempunyai wewenang membuat aturan harus segera menyelesaikan persoalan tersebut, bisa saja dengan membuat aturan lagi terkait dengan penyelesaian konflik pemira sesuai dengan wewenangnya dalam membuat aturan.
Sintesa itu pun dalam pemikiran dialektik secara otomatis menjadi tesa. Kemudian hadir pula antitesa, bahwa pemira telah berjalan bahkan pemungutan suara telah dilakukan sehingga aturan penyelesajan konflik tidak bisa dibuat sehingga pencari keadilan diterlantarkan oleh penyelenggara pemilu. Agar kejadian seperti ini di pemilihan yang akan datang bisa jelas penyelesaiannya, dan yang bertanggung jawab, selain KPRM, juga adalah DPM dan birokrasi. Maka, muncul sintesa yang meniscayakan dibentuknya mahkamah mahasiswa oleh DPM yang di SK-kan oleh birokrasi untuk penyelesaian sengketa pemira. Agar tidak mengambang, bahkan tak menimbulkan kerancuan (keinginan membawakannya ke PTUN. Masa iya, kita harus ke PTUN, apalagi sampai judicial review agar MK bisa menangani sengketa pemira), yang malah menambah panjang barisan kepedihan.
Pembentukan mahkamah mahasiswa setidaknya merupakan keputusan yang paling tepat sesuai dengan kondisi obyektif mahasiswa Unram saat ini. Apalagi hal tersebut begitu dibutuhkan oleh paslon nomor yang menuntut keadilan dan kepastian hukum dari KPRM, DPM dan birokrasi.
Dari sekelumit pemikiran di atas, penulis teringat dalam memperbandingkan logika dan dialektika Ueberweg menyatakan, bahwa kalau bertemu dengan perkara yang simpel, mudah, kita mesti pakai logika. Tetapi kalau berjumpa dengan perkara yang sulit, kompleks, kita mesti pakai perpaduan dua pertantangan. Seperti dialog Bung Didi dan Bung Wawan, hanya saja jangan pernah melepaskan diri terlalu jauh dari pokok persoalan obyektifnya. Sehingga apabila tidak melepaskan diri dari akar masalah terlalu jauh. Penulis melanjutkan dengan dalil Tan Malaka, jadi dalam daerah yang pasti ini, ialah dalam daerah salah satu pihak di antara dua pihak yang bertantangan, maka kita boleh menjalankan logika. Tetapi dalam abstraknya, pertanyaan tadi sudah tidak mampu diselesaikan logika. Kita mesti lari kepada dialektika.
“Tulisan ini diangkat dari diskusi panjang dengan teman seperjuangan (Maaf jika tulisan ini tidak sekiranya belum berhasil memecahkan kebuntuan pikiran kita dalam persoalan pemira ini. Itu berarti saya belum mampu mencerahkan pembaca).”
Oleh: Hasan (Mahasiswa FKIP Unram)